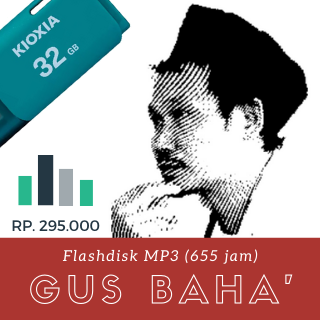Oleh M Abdullah Badri
Dutaislam.or.id - Di Jepara, Jawa Tengah, ada pesantren besar dimana madrasah berbasis salafnya (masuk kelas pukul 14.00-17.00 WIB) harus "dikorbankan" sejak para guru yang biasa mengajar di sana dimadu dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh kebijakan pemilik pesantren.
Jam mengajar Ilmu Nahwu, Sharaf, I'lal, I'rab, Fiqih, Tauhid, Hadits, Tafsir dan materi khas pesantren lainnya harus diberikan dulu ke siswa di SMK, pagi hingga siang hari. SMK lebih prioritas katanya. Para guru ngaji salaf bahkan bisa sibuk seharian jika mereka dapat tambahan jam ngajar di MTs dan MA. Apabila sang guru agama yang pintar kitab kuning tersebut harus dijadual lagi ngisi ngaji kitab di pesantren, waktu luang buat keluarganya bahkan habis.
Jika hanya keluarga saja yang dikorbankan demi mengajar, itu hal wajar di pesantren. Dalam mengabdi di pesantren, waktu tidak bisa dihitung dengan matematika uang, gaji tidak dihitung rumit. Namun, jika yang jadi korban adalah madrasah salafnya, tentu hal itu sangat merugikan santri-santri salaf di pesantren itu, hingga akhirnya banyak yang boyong di tengah jalan dan gethun (kecewa) karena dianggap tak mendapatkan perhatian kiai.
Bayangkan, ada seorang santri yang wadul (mengadu) ke saya kalau sejak kehadiran SMK di ponpes itu, kitab-kitab yang mereka beli ingin dijual kembali dengan dalih tidak ada asahan makna gandhul pegon (alias masih mulus dan nampak baru) karena, eh, karena sang guru ngaji di kelas salaf hampir tidak hadir sekian puluh kali dalam sekian bulan.
Acapkali, jam ajar yang hanya tiga jam di madrasah salaf habis digunakan tidur para siswa santri di kelas karena lelah menunggu jadual masuk mengajar gurunya yang tak kunjung hadir. Hilangkan penat di kelas, ada yang ngaji sendiri, njajan, ngerumpi bersama santri lain hingga akhirnya pulang tanpa proses belajar.
Keadaan itu berlangsung lama hingga memunculkan tangis bersama antar santri dan atau santriwati di gothakan (kamar) masing-masing. Mereka menangis kala mengingat jerih payah orang tua yang berniat serius memasukkan mereka ke madrasah salaf yang alumninya banyak jadi tokoh dan ulama berpengaruh. Dari rumah diragati ayah-ibu, di pesantren dibrondholi harapannya. Sedih.
Karena masuknya siang, tiap pagi, para santri salaf di pesantren itu "terpaksa" harus menerima tugas dari kiai sebagai koki masak buat adik-adiknya di MTs, MA, MAK, menyiapkan jatah makan mereka yang jumlahnya ribuan, dibantu kang-kang khadim pondok yang memang hidup di pesantren untuk mengabdi ke kiai.
Karena pengabdian itulah, di siang hari, mereka sudah kecapekan. Daya serap pengetahuan jadi menurun. Dalam kondisi lelah, mereka harus masuk ke kelas. Sama dengan mereka, guru yang masuk mengajar juga sudah kelelahan. Pegel ngajar santri lain di kelas lain sejak pagi.
Ya, madrasah salaf sore akhirnya dikelola sekenanya. Ketika jadi muthkhorrijin (alumni), -saya banyak mendengar dari mereka,- sangat jarang yang bangga atas almamater. Ikatan batin tergerus karena sistem yang tidak dikelola dengan baik.
Imajinasi belajar ala pesantren, -yang seharusnya memberi warisan ilmu pengetahuan agama dan tawadlu' serta khidmah kepada kiai dengan sepenuh bathin,- lamat dan lamban, tercabik. Husnudzan harus ditemukan di tengah kekecewaan para alumni.
Kondisi yang saya rekam di atas terjadi jauh sebelum ada kontroversi Full Day School (FDS) yang ngotot ditabrakkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi "al-Muhammadiyah" ke publik. Saya ingin menujukkan bukti, kehadiran SMK saja sudah "membunuh" madin milik pesantren, apalagi FDS.
Sekolah Kerja
Tanpa kajian matang, Muhadjir terkesan menganggap rasional bahwa guru harus mengajar 40 jam sepekan, alias 8 jam sehari. Guru dan siswa mau dimakamkan di sekolah karena jam hidupnya di luar sana, terpakas habis.
Dalam dunia medis pun, angka 40 jam itu mendekati maksium manusia normal bekerja harian, yang kata dr. H Ari Fahrial Syam, dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) hanya mampu bekerja maksimal 50 jam sepekan. Itu pun masih diharuskan mengonsumsi air putih dua liter sehari (10 gelas) agar terhindar dari dehidrasi dan tubuh drop. (http://bit.ly/aw240717). Apa sekolah akan pesan puluhan galon air sehari?
Lewat FDS, proses mencari ilmu akhirnya sama durasi dengan jam kerja di pabrik. Dan itu dipaksa oleh sistem, bukan minat personal. Bedanya, jika 8 jam kerja bisa dapat Rp. 50 ribu, di sekolah harus punya bekal yang hampir sama agar bisa hidup 8 jam di sekolah (kecuali ngirit dengan puasa dan pulang ngesot). Menjenuhkan, melelahkan, dan masih kena teror mental ujian semester dan ujian nasional.
Selain itu, - di luar besarnya minat santri madrasah salaf yang saya rekam kisah tragis harapannya di atas,- umumnya, ketika siswa masuk kelas, ia sedang memasuki ruang penuh kebosanan. Masuk kelas sudah dihantui pelajaran, karakter guru yang kadang killer serta tugas rumahan yang selalu membuat stres. Kala saya sekolah dulu, kabar yang paling bisa disambut gembira adalah "libur", "rekresasi", "jam kosong" dan "guru rapat bersama".
Di sekolah umum, guru agama paling tidak diminati. Di madrasah, guru agama yang paling disegani dan ditakuti rata-rata adalah guru nahwu yang materinya rumit bin jelimet itu. Karakter siswa memang tidak suka yang rumit, meski tidak semuanya. Wajar karena mereka menempuh usia dewasa dan jati diri. Apakah FDS ingin menambah kebosanan siswa di kelas, meski dengan bujukan kurikuler-kurikuler itu? Bukankah tempat tanpa gerakan itu adalah kuburan?
SPP nunggak, hal biasa di madin. Pihak madin tidak memberi sanksi dengan mengunci siswa tidak bisa ikut ujian. Andai saja ketika ujian siswa tidak masuk, ia bisa tunda kerjakan soal. Di madin, guru tidak banyak yang membincang nilai, tapi perilaku. Adab kepada guru sangat diperhatikan. Ini yang sulit ditemukan di sekolah formal pagi yang suasana kelas bejubel puluhan siswa dengan keperpaksaan masing-masing atas nama ijazah atau masa depan.
Di madin sore, siswa tiga biji diajar satu guru ngaji. Asal tidak dimadu saja dengan SMK seperti tragis diniyah salaf cerita saya di atas. Karena imbal jasa guru madin tidak layak disebut gaji, disebutlah bisyaroh (bebungah/hadiah seadanya). Adik saya yang ngajar di madin hanya dibisyaroh 100 ribu, cukup buat beli sabun, sampo atau minyak wangi sebulan, yang tiap sore habis aromanya dicium murid-murid madin lewat tangannya yang sangat dihormati.
Puluhan ribu guru madin setia menjalani itu, murid-murid juga sedia belajar, saling membutuhkan dalam menghilangkan kebodohan dan membangun karakter mulia, namun ingin dibungingahuskan secara sistematis melalui sistem FDS. Fantadziris saa'ah (tunggu kiamat) saja.
Layak diduga, FDS ala Muhadjir ingin membuat drop eksistensi pendidikan madrasah diniyah, yang tanpa dikoreksi pun banyak gulung tikar seperti kisah madrasah salaf yang dimadu SMK itu. Mau apa sih dia?
Jika Muhadjir percaya bahwa tumbuhnya karakter kuat itu ada di pendidikan agama, mengapa dia tidak memilih Full Diniyyah School (FDS), yang mewajibkan guru sekolah mengajar materi akhlak dan agama 25 jam sekalian? Itu lebih konkrit daripada "membunuh" hidup-hidup madin dan TPQ dengan kebijakan ambisius tanpa visi jelas. Pilih memakamkan FDS atau memakamkan diniyah? [dutaislam.or.id/ab]
M Abdullah Badri, mukim di Jepara
Keterangan:
Naskah artikel ini pernah dimuat di Buletin Aulawi Edisi 04, Jumat, 28 Juli 2017. Versi mobile Buletin Aulawi dapat diunduh di http://bit.ly/2vVGl9L