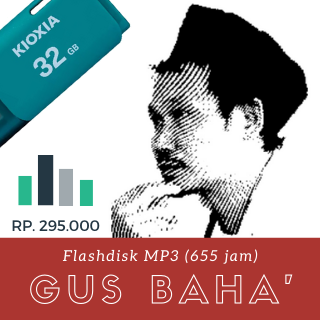|
| Salah kaprah memahami konsep hijrah |
Oleh M Abdullah Badri
Dutaislam.or.id - Tidak disebutkan siapa yang mengawali istilah hijrah dalam gerakan “pindah” dari tabiat lama kepada tabiat baru yang dianggap lebih saleh di kalangan muda kampus dan urban. Bukti akun (instagram dan facebook) bertajuk pemuda hijrah hingga mencapai jutaan followers, dan menjamurnya komunitas hijrah di kampus-kampus, cukuplah sebagai alasan untuk menyebutnya sebagai budaya populer. Dan karena sifatnya selalu dilandaskan dengan kesalehan spiritual, tidak berlebihan jika disebut pula sebagai spiritualitas populer (pop).
Dalam kajian Cultural Studies, budaya pop setidaknya mensyaratkan pemenuhan unsur homogenitas (seragam), sharabilitas (umum dipakai), dan juga durabilitas (kesementaraan). Tidak ada penghayatan reflektif atas spiritualitas yang masuk ke dalam gelanggang budaya pop. Meski spirit perubahan individu tetap tidak dipungkiri.
Dalam bahasa umum, mereka yang sedang hijrah itu sebetulnya sedang mendalami masa pertobatan, pindah dari pribadi berkarakter tidak saleh menjadi karakter yang lebih baik, lebih saleh, dan tentunya, lebih sadar nilai-nilai moral agama. Namun, baru beberapa tahun belakangan ini, kata hijrah disematkan untuk fenomena pertobatan di kalangan muda tersebut, saking massal dan massifnya fenomena itu diikuti.
Dari penamaan saja, kata hijrah sudah mengandung artikulasi “berpindah”, mengikuti jejak perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yastrib (Madinah) yang didahului munculnya potensi ancaman fisik dan pembunuhan dari suku Quraish yang merasa terancam pengaruhnya.
Dalam konteks hijrah Nabi, tidak ada paradigma berpindah menjadi yang lebih saleh. Nabi berhijrah karena perintah wahyu, dan paradigmanya adalah berpindah tempat agar dakwahnya lebih meluas dan lebih baik.
Ada proses gradual dalam hijrah Nabi. Selain menunggu turunnya wahyu, Nabi juga menyiapkan segalanya, belajar siap dulu. Ketika sahabat dekat (khalil) nya Nabi, Abu Bakar Asshiddiq r.a, mendesak untuk berhijrah pun, Nabi tidak langsung mengiyakan.
Dalam seri buku Sirah Nabawiyah “Abu Bakr Asshiddiq yang Lembut Hati”, yang ditulis Muhammad Husain Haikal (2003), Nabi justru menjawab Abu Bakar dengan spirit untaian kalimat sabar, “Jangan tergesa-gesa (hijrah), kalau Allah nanti memberikan seorang teman kepadamu”. (hlm: 13).
Sementara itu, para sahabat lain yang sudah tidak kuat menghadapi ancaman dan siksaan Quraisy sudah ada yang hijrah ke wilayah Abisinia. Abu Bakar sempat terpikir akan mengikuti jejak hijrah sahabat Nabi ke Abisinia sebelum akhirnya dicegah oleh Rabiah ibn ad-Dughunnah karena dia diminta supaya lebih dekat dengan Nabi mengingat Abu Bakar lah yang selama Nabi berjuang di Makkah selalu menjadi pendamping dan penolong utama.
Ketika sudah mendapatkan perintah hijrah pun, Nabi tidak langsung melakukan perjalanan sebelum meminta Abu Bakar untuk menyiapkan segalanya. Nabi tidak pernah tergesa-gesa dalam perjalanan hijrahnya. Jadi, dalam hijrah Nabi, hijrah itu tidak spontan dan instan, apalagi bernuansa hanya mengikuti arus, alias ngepop.
Pemaknaan anarkhis ala Khawarij ini menyerukan bahwa mereka yang bisa disebut masih Islam adalah yang mau bergabung dalam “darul islam” kelompok ini. Sebaliknya, yang tidak mau hijrah (bergabung) dengan jalan Khawariji masuk kategori “darul harb” (negara perang), yang harus dimusnahkan. Spirit hijrah nya sudah bergeser. Dari yang semula “berpindah dari tempat yang lebih aman” menjadi “bergabung kepada kelompok surga atau golongan neraka” ala mereka.
Paradigma surga dan neraka itulah yang nampaknya muncul dalam fenomena iconic hijrah di kalangan pemuda urban yang haus spiritualitas akibat kejenuhan mengalami rutinitas modernisme, baik di kantor maupun di kampus.
Laku hijrah ala urban itu pun akhirya tidak mengekspresikan jiwa terdalam pengamalnya karena sudah menjadi budaya populer yang siapa saja meng-arus bersama, dengan mengikuti petuah-petuah para figur ustadz layar datar internet beserta ajaran-ajaran “langsung jadi” via gadget.
Muncullah grup-grup di jaringan anak muda bertajuk one day one juz, one day one hadits, ramai-ramai berhijab (dulunya jilbab), latah menumbuhkan jenggot, hingga gaya hidup lain yang mencerminkan dirinya terkesan lebih syar’i daripada yang lain.
Gerakan bergabung dengan gaya spiritualitas pop hijrah urban ini pun memunculkan egoisme spiritual sebagai yang “paling saleh”. Mereka yang tidak bergabung, disebut sebagai orang sana (osan), yang jelas berbeda dengan orang sini (osin). Mereka yang tidak bergabung pun harus “dimuallafkan kembali” karena masih dalam lingkaran “darul harbi” Khawariji.
Semangat spritualisme pop ala hijrah terbukti mampu membawa seseorang yang awalnya tidak mengenal ajaran dan syariah agama bisa menjadi ustadz dadakan. Tidak paham makna Al-Qur’an, tapi berani memaknainya hanya karena belajar secara instan. Kesalahan yang pernah dilakukan Evie Evendi yang pernah menyebut Nabi pernah tersesat adalah contoh ironis terbaru.
Akibat tidak mengalami proses pembelajaran agama yang gradual dan kontinyu, fenomena hijrah urban mengakibatkan orang yang dulunya ada di ekstrim kiri langsung pindah meloncat di ekstrim kanan. Awalnya merasa berdosa, begitu hijrah, langsung lompat menjadi sosok merasa paling benar sendiri. Ekspresi spiritalitasnya nihil. Kesadaran beragamanya kalah dengan dominasi semangat ingin berubah tanpa diimbangi graduasi ngaji. Jadi ingat artis Sesar yang katanya mantap hijrah tapi putar balik lagi karena alasan-alasan apologetiknya. Duh. [dutaislam.or.id/ab]
Dutaislam.or.id - Tidak disebutkan siapa yang mengawali istilah hijrah dalam gerakan “pindah” dari tabiat lama kepada tabiat baru yang dianggap lebih saleh di kalangan muda kampus dan urban. Bukti akun (instagram dan facebook) bertajuk pemuda hijrah hingga mencapai jutaan followers, dan menjamurnya komunitas hijrah di kampus-kampus, cukuplah sebagai alasan untuk menyebutnya sebagai budaya populer. Dan karena sifatnya selalu dilandaskan dengan kesalehan spiritual, tidak berlebihan jika disebut pula sebagai spiritualitas populer (pop).
Dalam kajian Cultural Studies, budaya pop setidaknya mensyaratkan pemenuhan unsur homogenitas (seragam), sharabilitas (umum dipakai), dan juga durabilitas (kesementaraan). Tidak ada penghayatan reflektif atas spiritualitas yang masuk ke dalam gelanggang budaya pop. Meski spirit perubahan individu tetap tidak dipungkiri.
Dalam bahasa umum, mereka yang sedang hijrah itu sebetulnya sedang mendalami masa pertobatan, pindah dari pribadi berkarakter tidak saleh menjadi karakter yang lebih baik, lebih saleh, dan tentunya, lebih sadar nilai-nilai moral agama. Namun, baru beberapa tahun belakangan ini, kata hijrah disematkan untuk fenomena pertobatan di kalangan muda tersebut, saking massal dan massifnya fenomena itu diikuti.
Dari penamaan saja, kata hijrah sudah mengandung artikulasi “berpindah”, mengikuti jejak perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yastrib (Madinah) yang didahului munculnya potensi ancaman fisik dan pembunuhan dari suku Quraish yang merasa terancam pengaruhnya.
Dalam konteks hijrah Nabi, tidak ada paradigma berpindah menjadi yang lebih saleh. Nabi berhijrah karena perintah wahyu, dan paradigmanya adalah berpindah tempat agar dakwahnya lebih meluas dan lebih baik.
Ada proses gradual dalam hijrah Nabi. Selain menunggu turunnya wahyu, Nabi juga menyiapkan segalanya, belajar siap dulu. Ketika sahabat dekat (khalil) nya Nabi, Abu Bakar Asshiddiq r.a, mendesak untuk berhijrah pun, Nabi tidak langsung mengiyakan.
Dalam seri buku Sirah Nabawiyah “Abu Bakr Asshiddiq yang Lembut Hati”, yang ditulis Muhammad Husain Haikal (2003), Nabi justru menjawab Abu Bakar dengan spirit untaian kalimat sabar, “Jangan tergesa-gesa (hijrah), kalau Allah nanti memberikan seorang teman kepadamu”. (hlm: 13).
Sementara itu, para sahabat lain yang sudah tidak kuat menghadapi ancaman dan siksaan Quraisy sudah ada yang hijrah ke wilayah Abisinia. Abu Bakar sempat terpikir akan mengikuti jejak hijrah sahabat Nabi ke Abisinia sebelum akhirnya dicegah oleh Rabiah ibn ad-Dughunnah karena dia diminta supaya lebih dekat dengan Nabi mengingat Abu Bakar lah yang selama Nabi berjuang di Makkah selalu menjadi pendamping dan penolong utama.
Ketika sudah mendapatkan perintah hijrah pun, Nabi tidak langsung melakukan perjalanan sebelum meminta Abu Bakar untuk menyiapkan segalanya. Nabi tidak pernah tergesa-gesa dalam perjalanan hijrahnya. Jadi, dalam hijrah Nabi, hijrah itu tidak spontan dan instan, apalagi bernuansa hanya mengikuti arus, alias ngepop.
Hijrah kaum radikal
Hijrah kemudian berkembang maknanya dari “berpindah” menuju “berpindah dan bergabung” ketika kelompok aliran teologi Khawarij mengukuhkan tafsir teologis bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar sejatinya adalah kafir. Dan oleh karenanya harus dilenyapkan (Khazanah Intelektual Islam, Nurkholish Madjid, 1984: 11).Pemaknaan anarkhis ala Khawarij ini menyerukan bahwa mereka yang bisa disebut masih Islam adalah yang mau bergabung dalam “darul islam” kelompok ini. Sebaliknya, yang tidak mau hijrah (bergabung) dengan jalan Khawariji masuk kategori “darul harb” (negara perang), yang harus dimusnahkan. Spirit hijrah nya sudah bergeser. Dari yang semula “berpindah dari tempat yang lebih aman” menjadi “bergabung kepada kelompok surga atau golongan neraka” ala mereka.
Paradigma surga dan neraka itulah yang nampaknya muncul dalam fenomena iconic hijrah di kalangan pemuda urban yang haus spiritualitas akibat kejenuhan mengalami rutinitas modernisme, baik di kantor maupun di kampus.
Laku hijrah ala urban itu pun akhirya tidak mengekspresikan jiwa terdalam pengamalnya karena sudah menjadi budaya populer yang siapa saja meng-arus bersama, dengan mengikuti petuah-petuah para figur ustadz layar datar internet beserta ajaran-ajaran “langsung jadi” via gadget.
Muncullah grup-grup di jaringan anak muda bertajuk one day one juz, one day one hadits, ramai-ramai berhijab (dulunya jilbab), latah menumbuhkan jenggot, hingga gaya hidup lain yang mencerminkan dirinya terkesan lebih syar’i daripada yang lain.
Gerakan bergabung dengan gaya spiritualitas pop hijrah urban ini pun memunculkan egoisme spiritual sebagai yang “paling saleh”. Mereka yang tidak bergabung, disebut sebagai orang sana (osan), yang jelas berbeda dengan orang sini (osin). Mereka yang tidak bergabung pun harus “dimuallafkan kembali” karena masih dalam lingkaran “darul harbi” Khawariji.
Semangat spritualisme pop ala hijrah terbukti mampu membawa seseorang yang awalnya tidak mengenal ajaran dan syariah agama bisa menjadi ustadz dadakan. Tidak paham makna Al-Qur’an, tapi berani memaknainya hanya karena belajar secara instan. Kesalahan yang pernah dilakukan Evie Evendi yang pernah menyebut Nabi pernah tersesat adalah contoh ironis terbaru.
Akibat tidak mengalami proses pembelajaran agama yang gradual dan kontinyu, fenomena hijrah urban mengakibatkan orang yang dulunya ada di ekstrim kiri langsung pindah meloncat di ekstrim kanan. Awalnya merasa berdosa, begitu hijrah, langsung lompat menjadi sosok merasa paling benar sendiri. Ekspresi spiritalitasnya nihil. Kesadaran beragamanya kalah dengan dominasi semangat ingin berubah tanpa diimbangi graduasi ngaji. Jadi ingat artis Sesar yang katanya mantap hijrah tapi putar balik lagi karena alasan-alasan apologetiknya. Duh. [dutaislam.or.id/ab]
M Abdullah Badri, founder Marka Bangsa
(Lembaga Kajian Pemikiran dan Advokasi)