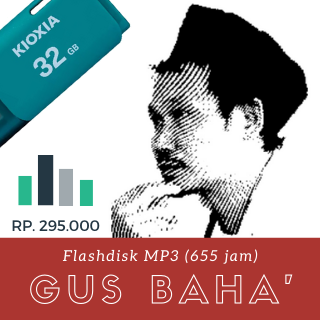|
| Jokowi dan Kiai Said. Foto: Geotimes.co.id. |
Oleh Nadirsyah Hosen
Dutaislam.or.id - Senar gitar itu kalau terlalu kencang akan mudah putus. Tetapi kalau terlalu kendor, suaranya akan sumbang. Maka, diperlukan sikap yang moderat, plus bacaan yang mumpuni atas konteks sosial politik yang dinamis. Itulah posisi yang selalu diambil Nahdlatul Ulama (NU) sepanjang sejarahnya.
Pemilihan presiden telah menyisakan ruang di mana politik identitas bisa berekspresi atas nama “reformasi” atau “transformasi”. Dalam menghadapi isu ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) harus rela “tidak populer” di masyarakat, atau bahkan warga Nahdliyin sendiri. PBNU merasa penting untuk melakukan langkah zigzag model dakwah, agar suasana kebatinan masyarakat yang menginginkan persatuan tetap terjaga. Inilah cara PBNU menjaga Indonesia.
Ekspresi dan perwujudan sikap moderat NU tidak berarti harus selalu sama dan tetap, namun bisa dengan lentur menghadapi perubahan zaman. Dijaga dengan pergumulan para kiai akan kaidah fikih, dibarengi interaksi yang intens dan terus menerus dengan masyarakat, membuat pilihan sikap NU sering gagal dipahami para pengamat.
Ambil contoh perkembangan sosial politik pasca pengumuman kabinet. Benar bahwa tidak satu pun representasi PBNU yang dimasukkan dalam kabinet. Nama-nama yang diminta dari PBNU oleh Presiden Joko Widodo sama sekali tidak digubris. Bahkan KH Ma’ruf Amin, selaku Wakil Presiden, tidak dimintai pandangan dalam penyusunan kabinet.
Secara halus, saat penyusunan dan pemanggilan calon menteri, beliau malah diminta Presiden pergi ke Jepang—sesuatu yang sebenarnya bisa diwakilkan oleh pejabat negara lainnya.
Pemanggilan para calon menteri, tanpa kehadiran Wakil Presiden, mempertontonkan secara nyata ke depan publik fatsun politik yang telah dilanggar. Seolah ini adalah Kabinet Jokowi, bukan Kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Ketika posisi Menteri Agama diberikan kepada selain NU, ternyata juga tidak ada penjelasan maupun komunikasi kepada para kiai NU yang sudah habis-habisan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam pilpres. Kontribusi mereka sama sekali tidak direken oleh Jokowi dan elite politik di sekitar beliau.
Para kiai terkejut dan tidak menyangka Jokowi bisa setega itu. Dalam pertemuan terbatas bersama 9 Kiai Khos Jawa Timur, Kiai Ma’ruf Amin tidak dapat memberi penjelasan yang meyakinkan akan sikap politik Jokowi seperti di atas—mungkin karena beliau pun heran dengan manuver Jokowi yang serasa “habis manis sepah dibuang”.
Selama ini para kiai bukan saja habis-habisan mendukung pasangan 01 di pilpres, tapi juga terus menjaga NKRI dari paham radikal. Maka, sudah sepatutnya Presiden berkonsultasi dengan para kiai, bukan malah, by design, membuat para kiai merasa seperti mendorong mobil mogok, yang setelah mesinnya hidup, mobil segera berlalu tanpa salam, apalagi mengajak turut serta.
Tapi, benarkah Kiai NU mutung atau ngambek? Tidak. Para kiai selalu mengambil posisi “tidak terlalu bergembira atas apa yang diraih, dan tidak terlalu sedih atas apa yang lepas.” Inilah sikap zuhud keagamaan yang juga terwujud dalam politik. Yang dipikirkan oleh para kiai sebenarnya, paling tidak, ada dua hal utama.
Pertama, selama ini pemerintah terkesan membiarkan gerakan radikal, itulah sebabnya para kiai NU, termasuk kepanjangan tangan mereka seperti Gerakan Pemuda Ansor, hadir di depan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika negara sudah menyatakan hadir untuk melawan gerakan radikal, maka Banser kembali ke kandang, akademisi NU kembali ke kampus, dan para kiai kembali fokus ke pesantren. NU memberi kesempatan untuk pemerintah berdiri di depan melawan gerakan radikal.
Kedua, PBNU kembali fokus kepada urusan pemberdayaan umat, termasuk di dalamnya menyeimbangkan kekuatan gerakan sosial politik di luar pemerintahan. Dalam demokrasi keseimbangan ini penting.
Ibarat kata, jikalau ada badai menerpa kapal, di saat para penumpang berlari semua ke arah depan, maka agar kapal tidak oleng, PBNU malah berlari ke arah belakang demi menjaga keseimbangan.
Menolak mafsadah (kejelekan) lebih diutamakan ketimbang mengambil keuntungan. Begitu kaidah fikih menginspirasi PBNU. Di saat kursi kekuasaan dibagi begitu saja, hingga lawan politik seperti Prabowo diberi posisi terhormat, PBNU mengambil posisi menolak efek negatif pemerintahan tanpa keseimbangan pendapat. Dominasi kekuasaan yang berlebihan tidak baik untuk demokrasi.
Jika ada dua pilihan yang buruk, ambil yang paling kecil keburukannya. Ketika Front Pembela Islam (FPI) yang selama ini menyalurkan aspirasi politiknya ke Prabowo, tiba-tiba ditinggal oleh Prabowo yang masuk kabinet, PBNU mengambil risiko yang paling kecil keburukannya, dengan mengulurkan salam persahabatan kepada Habib Rizieq Shihab, imam besar FPI, untuk sama-sama kembali fokus mengurusi umat.
Keburukan yang lebih besar yang tengah diantisipasi itu adalah ketika aspirasi kelompok 212, yang ditinggal Prabowo, menjadi bola liar yang bisa merugikan umat dan bangsa. PBNU memilih bahaya yang lebih ringan. Bagaimanapun FPI adalah saudara kita semua.
Kalau Presiden Jokowi saja bisa merangkul Pak Prabowo dalam kabinet, tentu tidak masalah kalau PBNU juga bisa menerima FPI. Sesama anak bangsa hidup rukun itu hal yang baik-baik saja.
Namun, sikap NU tetap kukuh soal penghormatan terhadap negara hukum. Menolak ideologi khilafah atau komunis yang hendak mengganti Pancasila, serta menolak ujaran kebencian dan berita hoks. Pernah KH Hasyim Muzadi (Allah yarham) suatu saat dawuh: “kalau terlalu jauh dengan pemerintah, sulit untuk amar ma’ruf. Terlalu dekat, sulit untuk nahi munkar.”
Berbagai sikap PBNU belakangan ini seolah mengajak kita memandang Kiai Ma’ruf Amin dan Prabowo yang berada di dalam pemerintah untuk amar ma’ruf. Sementara, dengan kacamata yang sama, kita bisa memandang PBNU (dan FPI serta LSM misalnya) yang di luar pemerintah untuk menjalankan nahi munkar. Semuanya elok dan baik-baik saja.
Keseimbangan sosial politik menjadi tercipta. Misalnya ketimpangan sosial, korupsi, ketidakadilan hukum, dan lemahnya literasi menjadi persoalan kita bersama, yang membutuhkan kerjasama semua elemen anak bangsa.
Tapi, apakah NU akan meninggalkan posisinya menjaga NKRI? Kaidah lain mengatakan “sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya”. PBNU tidak meninggalkan perjuangan menjaga NKRI, namun arah perjuangannya kembali ke basic, yaitu memberdayakan umat di tengah musim pancaroba politik. Ingat ya, kita harus memberdayakan, bukan memperdayakan. Soalnya, gara-gara hanya beda satu huruf, tapi efeknya bisa panjang, lho! [dutaislam.or.id/pin]
Dutaislam.or.id - Senar gitar itu kalau terlalu kencang akan mudah putus. Tetapi kalau terlalu kendor, suaranya akan sumbang. Maka, diperlukan sikap yang moderat, plus bacaan yang mumpuni atas konteks sosial politik yang dinamis. Itulah posisi yang selalu diambil Nahdlatul Ulama (NU) sepanjang sejarahnya.
Pemilihan presiden telah menyisakan ruang di mana politik identitas bisa berekspresi atas nama “reformasi” atau “transformasi”. Dalam menghadapi isu ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) harus rela “tidak populer” di masyarakat, atau bahkan warga Nahdliyin sendiri. PBNU merasa penting untuk melakukan langkah zigzag model dakwah, agar suasana kebatinan masyarakat yang menginginkan persatuan tetap terjaga. Inilah cara PBNU menjaga Indonesia.
Ekspresi dan perwujudan sikap moderat NU tidak berarti harus selalu sama dan tetap, namun bisa dengan lentur menghadapi perubahan zaman. Dijaga dengan pergumulan para kiai akan kaidah fikih, dibarengi interaksi yang intens dan terus menerus dengan masyarakat, membuat pilihan sikap NU sering gagal dipahami para pengamat.
Ambil contoh perkembangan sosial politik pasca pengumuman kabinet. Benar bahwa tidak satu pun representasi PBNU yang dimasukkan dalam kabinet. Nama-nama yang diminta dari PBNU oleh Presiden Joko Widodo sama sekali tidak digubris. Bahkan KH Ma’ruf Amin, selaku Wakil Presiden, tidak dimintai pandangan dalam penyusunan kabinet.
Secara halus, saat penyusunan dan pemanggilan calon menteri, beliau malah diminta Presiden pergi ke Jepang—sesuatu yang sebenarnya bisa diwakilkan oleh pejabat negara lainnya.
Pemanggilan para calon menteri, tanpa kehadiran Wakil Presiden, mempertontonkan secara nyata ke depan publik fatsun politik yang telah dilanggar. Seolah ini adalah Kabinet Jokowi, bukan Kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Ketika posisi Menteri Agama diberikan kepada selain NU, ternyata juga tidak ada penjelasan maupun komunikasi kepada para kiai NU yang sudah habis-habisan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam pilpres. Kontribusi mereka sama sekali tidak direken oleh Jokowi dan elite politik di sekitar beliau.
Para kiai terkejut dan tidak menyangka Jokowi bisa setega itu. Dalam pertemuan terbatas bersama 9 Kiai Khos Jawa Timur, Kiai Ma’ruf Amin tidak dapat memberi penjelasan yang meyakinkan akan sikap politik Jokowi seperti di atas—mungkin karena beliau pun heran dengan manuver Jokowi yang serasa “habis manis sepah dibuang”.
Selama ini para kiai bukan saja habis-habisan mendukung pasangan 01 di pilpres, tapi juga terus menjaga NKRI dari paham radikal. Maka, sudah sepatutnya Presiden berkonsultasi dengan para kiai, bukan malah, by design, membuat para kiai merasa seperti mendorong mobil mogok, yang setelah mesinnya hidup, mobil segera berlalu tanpa salam, apalagi mengajak turut serta.
Tapi, benarkah Kiai NU mutung atau ngambek? Tidak. Para kiai selalu mengambil posisi “tidak terlalu bergembira atas apa yang diraih, dan tidak terlalu sedih atas apa yang lepas.” Inilah sikap zuhud keagamaan yang juga terwujud dalam politik. Yang dipikirkan oleh para kiai sebenarnya, paling tidak, ada dua hal utama.
Pertama, selama ini pemerintah terkesan membiarkan gerakan radikal, itulah sebabnya para kiai NU, termasuk kepanjangan tangan mereka seperti Gerakan Pemuda Ansor, hadir di depan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika negara sudah menyatakan hadir untuk melawan gerakan radikal, maka Banser kembali ke kandang, akademisi NU kembali ke kampus, dan para kiai kembali fokus ke pesantren. NU memberi kesempatan untuk pemerintah berdiri di depan melawan gerakan radikal.
Kedua, PBNU kembali fokus kepada urusan pemberdayaan umat, termasuk di dalamnya menyeimbangkan kekuatan gerakan sosial politik di luar pemerintahan. Dalam demokrasi keseimbangan ini penting.
Ibarat kata, jikalau ada badai menerpa kapal, di saat para penumpang berlari semua ke arah depan, maka agar kapal tidak oleng, PBNU malah berlari ke arah belakang demi menjaga keseimbangan.
Menolak mafsadah (kejelekan) lebih diutamakan ketimbang mengambil keuntungan. Begitu kaidah fikih menginspirasi PBNU. Di saat kursi kekuasaan dibagi begitu saja, hingga lawan politik seperti Prabowo diberi posisi terhormat, PBNU mengambil posisi menolak efek negatif pemerintahan tanpa keseimbangan pendapat. Dominasi kekuasaan yang berlebihan tidak baik untuk demokrasi.
Jika ada dua pilihan yang buruk, ambil yang paling kecil keburukannya. Ketika Front Pembela Islam (FPI) yang selama ini menyalurkan aspirasi politiknya ke Prabowo, tiba-tiba ditinggal oleh Prabowo yang masuk kabinet, PBNU mengambil risiko yang paling kecil keburukannya, dengan mengulurkan salam persahabatan kepada Habib Rizieq Shihab, imam besar FPI, untuk sama-sama kembali fokus mengurusi umat.
Keburukan yang lebih besar yang tengah diantisipasi itu adalah ketika aspirasi kelompok 212, yang ditinggal Prabowo, menjadi bola liar yang bisa merugikan umat dan bangsa. PBNU memilih bahaya yang lebih ringan. Bagaimanapun FPI adalah saudara kita semua.
Kalau Presiden Jokowi saja bisa merangkul Pak Prabowo dalam kabinet, tentu tidak masalah kalau PBNU juga bisa menerima FPI. Sesama anak bangsa hidup rukun itu hal yang baik-baik saja.
Namun, sikap NU tetap kukuh soal penghormatan terhadap negara hukum. Menolak ideologi khilafah atau komunis yang hendak mengganti Pancasila, serta menolak ujaran kebencian dan berita hoks. Pernah KH Hasyim Muzadi (Allah yarham) suatu saat dawuh: “kalau terlalu jauh dengan pemerintah, sulit untuk amar ma’ruf. Terlalu dekat, sulit untuk nahi munkar.”
Berbagai sikap PBNU belakangan ini seolah mengajak kita memandang Kiai Ma’ruf Amin dan Prabowo yang berada di dalam pemerintah untuk amar ma’ruf. Sementara, dengan kacamata yang sama, kita bisa memandang PBNU (dan FPI serta LSM misalnya) yang di luar pemerintah untuk menjalankan nahi munkar. Semuanya elok dan baik-baik saja.
Keseimbangan sosial politik menjadi tercipta. Misalnya ketimpangan sosial, korupsi, ketidakadilan hukum, dan lemahnya literasi menjadi persoalan kita bersama, yang membutuhkan kerjasama semua elemen anak bangsa.
Tapi, apakah NU akan meninggalkan posisinya menjaga NKRI? Kaidah lain mengatakan “sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya”. PBNU tidak meninggalkan perjuangan menjaga NKRI, namun arah perjuangannya kembali ke basic, yaitu memberdayakan umat di tengah musim pancaroba politik. Ingat ya, kita harus memberdayakan, bukan memperdayakan. Soalnya, gara-gara hanya beda satu huruf, tapi efeknya bisa panjang, lho! [dutaislam.or.id/pin]
Nadirsyah Hosen, Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia – New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School, Australia. Esai ini disadur dari geotimes.co.id dengan judul asli 'Posisi NU dan Keseimbangan Sosial-Politik'