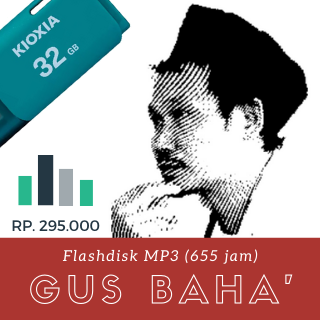|
| Cara Santri Menunjukkan Sikap Nasionalis. Foto: istimewa. |
Oleh Moh. Mahmud
Dutaislam.or.id - Selamat datang di tanah kami: Indonesia. Tanah surga yang membuat para bule ngiler memilkinya. Di sana kami jeritkan tangis pertama kami. Di sana kami menghabiskan masa-masa kecil yang penuh cerita. Di sana bapak-ibu kami bertani aneka sayur dan buah-buahan. Bukan hanya ingin menghidupi diri sendiri, tetapi untuk banyak orang di tanah kami. Tanpa peduli apakah orang-orang berterima kasih atau malah mencaci maki.
Di tanah itu pula, kami dikenalkan dengan angka dan aksara. Tiap pagi, kami dengar pesan sederhana dari bapak-ibu kami: "Jadilah anak yang berbakti pada agama, orang tua, dan tidak terkecuali tanah tumpah darahmu ini". Pesan sederhana itu yang selalu jadi sarapan bergizi bagi kami sebelum melangkah, memenuhi panggilan guru kami.
Sambil menyusuri sawah, kami tanamkan mimpi-mimpi. Meneguhkan tekad bersama burung-burung yang sedang bernyanyi. Kami mendapatkan banyak salam dari semesta. Aneka hewan dan tumubuhan sepertinya menyatukan harapan pada kami. Seakan mereka semua berkata: "Wahai anak harapan negeri, kelak kau akan jadi penyelamat kami. Kau yang akan memakmurkan kami. Yakinkan diri: mulailah dengan mencintai tanah airmu ini".
Baca: Melacak Tradisi Nasionalisme Asia Tenggara, Membangun Madrasah dan Defensifitas Salafiyah
Tiba saatnya guru kami bercerita tentang masa lalu tanah kami ini; tanah yang dulunya dikuasai orang-orang asing. Selama berabad-abad, para penjajah mempekerjakan kakek-nenek kami tiada henti. Hasil tani dirampas untuk kepentingan kolonial. Kerja rodi membuat kakek-nenek kami mati kelaparan. Para pejuang yang pemberani tidak kuasa melihat tangis di tanah ini. Sekalipun darah harus mengalir, perlawanan terus berkobar di mana-mana karena ini tanah kami sendiri. Begitu murah harga nyawa karena membela tanah air jauh lebih berharga.
Memang begitulah kalau cinta tanah air sudah mendarah-daging. Perlawanan terhadap para penjajah—yang memiliki persenjataan yang lengkap—oleh para pahlawan di berbagai penjuru adalah bukti nyata bahwa maut tidak apa-apanya dibandingkan tanah air yang harus jadi korbannya. Dan dalam hal ini, tidak terkecuali perlawanan dari kalangan pesantren. Para Kiai dan santri merupakan komunitas anti kolonial yang tidak pernah surut memberontak terhadap para penjajah.
Tidak berlebihan kiranya apabila George McTurnan Kahim (sebagaimana dikutip Zainul Milal Bizawi) menyimpulkan bahwa pesantren sebagai tradisi Islam di Nusantara merupakan akar nasionalisme Indonesia. Begitu juga dengan Dr. Setia Budi, yang lebih dikenal dengan Douwes Dekker, menyatakan secara konsisten patriotisme Indonesia tidak akan sehebat seperti yang diperlihatkan hingga mencapai kemerdekaannya, jika bukan karena pengaruh dan didikan agama Islam (pesantren, red).
Resolusi Jihad dan Tegaknya NKRI
Perlu kiranya dintandaskan bahwa kiprah pesantren memang tidak bisa dianggap remeh. Hal itu dapat dilihat dari keterlibatan tokoh-tokoh pesantren dalam pergerakan Nasional seperti pendiri Syarikat Islam, organisasi politik pertama di Hindia Belanda, yaitu H. Samanhudi dan H. Oemar Said Tjokroaminoto. Keduanya terlahir dari rahim pesantren.
H. Samanhudi adalah santri Pesantren Buntet, Cirebon dan H. Oemar Said (keturunan Kiai Kasan Besari) adalah santri Tegalsari, Ponorogo. Ada juga Suwardi Suryaningrat—yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara— juga nyantri di Pesantren Kalasan Prambanan asuhan Kiai Sulaiman Zainuddin. Bahkan pengaruh dunia pesantren berhasil mengubah pikiran Douwes Dekker. Sekalipun ia adalah keturunan Belanda yang akan menghancurkan Indonesia, ia memilih untuk bergabung dan bisa dikatakan jiwa tanah airnya kadang melebihi rakyat Indonesia sendiri.
Para kiai sangat yakin bahwa Indonesia akan segera menjemput kemerdekaannya. Keoptimisan itu sepertinya diperoleh dari dimensi supranatural para kiai. Para kiai juga tiada henti melakukan semedi (tirakat) untuk kemerdekaan Bangsa Indonesia seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Chasbullah Said, Pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, ayahanda Kiai Wahab.
Beliau menuliskan sebuah pesan di menara masjid yang ditutupi kain. Beliau berpesan bahwa jangan ada yang sampai membuka tulisan di balik kain itu. Kemudian menjelang akhir hayat, beliau berwasiat bahwa jika beliau wafat, mintalah Kiai Wahab untuk membuka tulisan di balik kain itu di tahun 1948. Kemudian tibalah tahun 1948, Kiai Wahab dengan didampingi para santri yang melantunkan shalawat burdah membuka kain itu dan didapatkan sebuah ukiran bertuliskan abjad arab ha’, ra’, ta’, dan mim.
Kiai Wahab pun memperhatikan tulisan itu dan akhirnya beliau mengerti bahwa tulisan itu—bila dirangkaikan—menjadi hurrun tammun yang bermakna kemerdekaan yang sempurna. Dan ternyata pesan Kiai Chasbullah Said bukan hanya omong kosong. Tepat pada tahun 1948, kemerdekaan Indonesia telah diakui dunia. Agresi militer Negeri Kincir Angin juga berhasil dipukul mundur.
Ketika detik-detik tegaknya Indonesia sebagai sebuah negara, Kiai dan santri tampil sebagai bagian inti untuk mengguyur kekuasaan kolonial hingga tiba suatu masa di mana Belanda harus angkat kaki dari tanah air ini. Komunitas santri memang pihak anti kolonial yang tetap merawat tradisi pemberontakan dan menempatkan visi perlawanan tidak hanya pada kepentingan sepihak saja, tetapi juga untuk tegaknya agama Islam. Perang Jawa sebagai perang besar sepanjang sejarah adalah bukti bahwa para Kiai dan santri memang punya nyali untuk terus mengobarkan semangat juang melawan kolonial Belanda.
Pasca tertangkapnya Pangeran Dipenogoro, gerakan perlawanan dari para Kiai dan santri bukannya reda, tetapi malah semakin bertubi-tubi. Ada sekitar 130 pertempuran yang terjadi setelah Pangeran Dipenogoro ditangkap. Pada awal abad ke-19 tiap ulama mempunyai kader-kader yang siap untk melanjutkan perjuangan. Kita bisa lihat Syekh Yusuf al-Makassari yang digantikan oleh Syekh Nawawi al-Banteni.
Baca: Sejarah Konstribusi Pesantren dan Kiai Untuk NKRI
Kiai Sholeh Darat yang menggantikan perjuangan ayahandanya sendiri Kiai Umar Semarang. Dan Kiai Abbas Buntet yang menjadi kader dari perjuangan Kiai Muta’ad, Kiai Hasyim Asy’ari, dan Kiai Wahab Chasbullah. Dari proses kaderisasi yang konsisten itu, akirnya terbentuklah Jam'iyyah Nahdlatul Ulama sebagai terjemahan intensif dari pada kobaran semangat komunitas santri Nusantara. Organisasi besar itu menyumbang kontribusi besar terhadap pergerakan Nasional dan tegaknya NKRI.
Segala gerakan perlawanan yang dilakukan para Kiai dan santri sebenarnya berkutat pada laskar Hizbullah. Di saat Jepang berkuasa dan di waktu yang sama Jepang juga didesak oleh tentara Sekutu, para Kiai memanfaatkannya demi menyongsong kemerdekaan Indonesia.
Pemanfaatan peluang itulah yang mengilhami terbentuknya laskar Hizbullah yang akan mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jepang sendiri mengakui bahwa kalangan Islam—atau lebih tepatnya pesantren—berada pada posisi yang strategis dalam mengupayakan sebuah kemerdekaan.
Para Kiai dan santri yang tergabung dalam laskar Hizbullah berada di barisan depan dalam menyambut euforia era revolusi kemerdekaan hingga tiba saat ditandatanganinya fatwa jihad oleh Kiai Hasyim Asy’ari pada 17 September 1945 dan kemudian pada 21-22 Oktober 1945 dilanjutkan dengan rapat konsolidasi atau lebih dikenal dengan Resolusi Jihad dengan dihadiri oleh para Kiai.
Lebih tepatnya, di samping sebagai penggerak semangat perjuangan, diusungnya Resolusi Jihad itu bertujuan bagaimana pihak pemerintah seharusnya mengambil sikap tegas terhadap pihak asing yang mencoba menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Surabaya, 10 November 1945 adalah saksi bisu akan ketangguhan para Kiai dan santri yang berada di garda terdepan dalam menghadang kedatangan kolonial.
Fatwa Jihad yang ditandaskan dengan Resolusi Jihad menjadikan komunitas sarungan (pesantren, red) semakin vokal menyuarakan perjuangan demi tegakknya NKRI. Meskipun jihad 10 November 1945 tidak sesuai harapan, dan pasukan Sekutu dapat menguasai seluruh wilayah Surabaya, tetapi pada akhirnya dunia internasional mengakui kedaulatan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Resolusi Jihad memang kenangan berharga sebagai epilog dari rentetan kisah perlawanan anti kolonial yang digerakkan oleh Kiai dan santri.
Dunia Pendidikan yang “Lupa Ingatan”
Mari hadirkan wacana untuk kembali bersama-sama menerjemahkan nasionalisme secara kreatif dan bertanggungjawab untuk kembali mengingat bahwa berjuang memulihkan dunia pendidikan adalah bagian dari cinta tanah tumpah darah.
Pendidikan sering “didengungkan” sebagai penentu kemajuan Bangsa. Setiap tanggal 21 Oktober, Bangsa ini memperingati Hari Pendidikan Nasional. Seolah dengan semangat yang berkobar kita hendak ingin mengakatan kepada alam semesta bahwa dengan pendidikan kita akan menjemput kesejahteraan. Tapi kini, rupanya pendidikan hanya sebagai bentuk akumulasi kekecewaan dan cobaan yang mengakibatkan luka yang begitu mendalam.
Kini, dunia pendidikan seolah “gegar otak” dengan orientasinya sebagai “pendidik” guna melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir yang akhirnya dapat membentuk karakter dengan dilandasi moral yang tinggi. Para generasi akan terlahir dari rahim pendidikan termasuk para koruptor. Tapi apa lacur, ada banyak “kesalahan teknis” dalam dunia pendidikan sehingga membuat mereka tidak tahu membedakan mana yang yang milik sendiri dan milik orang lain. Pun bagaimana mungkin kita sukses menghasilkan generasi berbudi mulia, bila carut-marut pendidikan tidak kunjung reda.
Keberadaan nasionalisme sebagai ide modern yang masuk ke dalam kesadaran pribumi melalui lembaga pendidikan sering diarak sebagai urat nadi persatuan. Tetapi nampaknya, penegasan Soekarno, bahwa dari Sabang sampai Merauke bukan sekadar bentangan geografis, melainkan juga bentangan kesatuan tekad, kesatuan nasib, dan kesatuan cita-cita nasional, telah lama terlupakan.
Baca: Menguatkan Nasionalisme Kaum Sarungan Nusantara
Dari masa orde baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya dipahami sebagai bentangan wilayah belaka. Akibatnya, ekspresi nasionalisme sangatlah kerdil dan buta: "manusia Indonesia" tidak terlihat sebagai kumpulan manusia yang berwarna-warni dalam suku, agama, dan adat istiadatnya dan dipersatukan oleh kesamaan kehendak, nasib, dan cita-cita nasional. Rezim orde baru sibuk menggadaikan nasionalisme teritorial melawan separatisme. Ketimpangan ekonomi dan sosial antar penduduk maupun wilayah juga terjadi.
Alhasil, hingga detik ini, nasionalisme kerdil itulah yang diajarkan melalui lembaga pendidikan dengan ekspresi yang lebih banyak pada ritual nasionalisme yang hambar: upacara bendera, menghafal nama-nama pahlawan, jumlah provinsi, dan hari-hari nasional.
Lebih parah lagi, dengan jamaknya lembaga pendidikan yang tak “mendidik”, cita-cita besar nasionalisme Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan beradab diberangus. Begitupun sejumlah nilai yang terbangun dalam nasionalisme Indonesia juga dikerdilkan, seperti kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.
Ngaji pada Pesantren
Perjuangan pesantren melawan kolonial tidak hanya dicukupkan sampai di momentum Resolusi Jihad. Sejak berdiri sampai sekarang, pesantren senantiasa "sadar" bahwa penjajahan tidak selamanya harus berhadapan dengan timah panas, tetapi beragam “produk modernisasi” mampu membuat masyarakat Nusantara kurang waras.
Sampai saat ini, pesantren mewaspadai tangan-tangan kolonial yang masih bergentayangan di bumi Nusantara dengan tetap konsisten meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki akhlak berkualitas. Lalu pada akhirnya, lahirlah kader-kader Islam yang berjiwa nasionalis. Tidak heran jika saat ditanya oleh Soekarno apakah nasionalisme itu termasuk doktrin Islam, Kiai Wahab Chasbullah menyatakan bahwa apabila ajaran Islam dilaksanakan dengan benar pasti seorang muslim akan bermental nasionalis.
Lahan akhlak menjadi agenda besar dan serius bagi Bangsa ini untuk digarap. Dan hal itu yang (sesungguhnya) menjadi alasan bagi dunia pendidikan harus belajar pada pesantren. Gerak-gerik pesantren juga perlu dilibatkan dalam lingkungan pendidikan. Dan jalan keluar dari mental-mental maling itu adalah dengan revolusi moral atau pesantren menyebutnya dengan ta’dib, artinya pendidikan jiwa atau mental. Hal ini juga akan menjadi nutrisi untuk menggemukkan naluri kecintaan pada tanah air yang mendalam di hati manusia sebagai sebuah indikasi bahwa ia memiliki iman yang sejati.
Pesantren tidak pernah lepas dari beberapa karakteristik pendidikan yang telah dijalankannya. Zamakhsyari Dhofier mengajukan beberapa karakteristik yang melekat pada diri pesantren yang di antaranya adalah masjid dan seorang Kiai. Di antara karakteristik yang ada, pendidikan Nasional masih belum dapat mengoptimalisasi atau bahkan tidak ada.
Pertama, masjid. Sabenarnya, masjid merupakan tempat ibadah bagi kaum muslim. Di pesantren sendiri, masjid menjadi pusat kegiatan kaum santri. Bukan hanya ritual rutin, tapi transformasi keilmuan juga dilakukan di masjid. Pesantren sebagai benteng pertahanan juga tiada letihnya melakukan proses penguatan keimanan dalam menjalani kehidupan.
Sudah sewajarnya bagi pendidikan Nasional untuk mulai menyusupkan “suasana masjid” ke dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional. Nasib para generasi sebagai “raga” ditentukan oleh dirinya sendiri sebagai “jiwa”. Dari hal ini, kita mungkin akan mulai “mengebiri” beragam ketidakpatutan yang terjadi di tumpah darah ini. Sederhananya, semua ruang di sekolah harus bernuansa masjid.
Artinya, orientasi pendidikan tidak hanya berkutat pada dimensi intelektual, tapi juga dimensi emosional atau spiritual karena masjid adalah tempat mengabdikan diri secara totalitas dan manifestasi kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannnya.
Kedua, kiai. Ia adalah pemimpin dan tokoh sentral di dunia pesantren. Secara umum, kiai adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang agama. Kiai mempunyai peran strategis dalam upaya “penyelamatan” di era kekinian. Kiai senantiasa mengupayakan adanya interaksi aktif antara pengetahuan yang terus melampaui nalar manusia dengan tata nilai etika dan moral dalam agama.
Kredibilitas moral seorang kiai bisa dilihat dari ketaatannya melakukan ibadah dan pengetahuan agamanya. Kiai mampu memelihara pranata sosial serta berusaha keras menjaga hal-hal mendasar dalam pandangan hidup dan patokan nilai-nilai yang sudah ada.
Artinya, boleh-boleh saja pesantren membukakan pintu bagi globalisasi, tetapi di saat yang sama pesantren juga harus menyusun “pertahanan” untuk menyelamatkan diri. Kiai dengan tingginya kualitas akhlak yang dapat dijadikan sebagai pendidikan ¬keteladanan (uswah hasanah) merupakan jawaban terhadap krisis keteladanan yang melanda Bangsa ini sehingga ide nasionalisme hanya menjadi omong kosong.
Itu semua adalah tugas bagi setiap orang yang ikut andil dalam suksesi pendidikan Nasional. Misalkan para guru atau pimpinan lembaga pendidikan. Sosok kiai harus bisa “merasuki” mereka; bertakwa kepada Sang Pencipta, insan ilmiah sejati yang konsekuwen mengamalkan ilmunya, suri teladan yang utuh antara sandaran lahiriah dan batiniah, dan pembina mental yang mulia.
Dari dua karakteristik pesantren tersebut, bukan berarti harus meramaikan sekolah-sekolah di luar pesantren dengan pembangunan masjid serta memaksa para guru untuk memberikan ceramah di setiap kelas. Sama sekali tidak! Akan tetapi, ingin meyakinkan bahwa supaya rumah besar kita ini tidak lagi dihuni oleh manusia yang panjang tangan, maka pendidikan harus benar-benar mendidik; "menohok" hati sehingga tidak akan melahirkan generasi yang berkepribadian serakah.
Beginilah cara pesantren mengekspresikan kecintaannya pada Indonesia. Cinta pesantren pada tanah airnya tidak akan pernah reda. Mulai dulu, kini, dan sampai mati, cinta santri untuk negeri tumpah darah ini. Mari bersama-sama rapatkan barisan untuk menjemput perubahan. Proyek perubahan merupakan proyek kemanusaian ketika keserakahan menjadi watak pokok suatu bangsa yang diwarnai penindasan dan ketimpangan. Wallahu a’alam! [dutaislam.or.id/ab]
Moh. Mahmud, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
DAFTAR PUSTAKA
- Bizawi, Zainul Milal. 2016. Masterpiece Islam Nusantara. Ciputat: Pustaka Compass.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai. Jakarta: LP3ES.
- Hamka. 2015. Lembaga Hidup. Jakarta: Republika.
- Nahrawi, Amiruddin. 1960. Pembaharuan Pendidikan Pesantren. Yogyakarta: Gama Media.
- Sagala, H. Syaiful. 2013. Etika dan Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zuhri, Saifuddin. 1981. Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia. Bandung: PT. Al-Ma’arif.
Keterangan:
Naskah ini pernah dikirimkan penulis ke Panitia Hari Santri 2017, dengan judul asal: Kiai, Santri, dan Cinta yang Abadi.